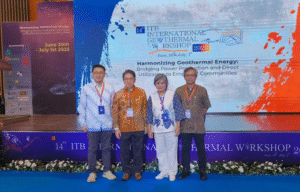MENITINI.COM-Beberapa waktu yang lalu, publik disuguhkan oleh berita adanya pengajuan uji materi atau judicial review terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni terkait dengan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi.
Secara historis dapat diketahui bahwa gugatan terhadap kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan ini bukanlah yang kali pertama dilakukan, mengingat sebelumnya telah ada 4 (empat) kali gugatan yang sama dan semuanya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan perkara tindak pidana korupsi maka tentunya dibutuhkan adanya pemikiran secara progresif tidak hanya dari sisi praktis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, namun juga dari segi legislasi atau peraturan perundang-undangan. Hal ini kian mendesak terutama mengingat bahwa kondisi negara Indonesia tidak sedang baik-baik saja melainkan berada dalam status darurat korupsi.
Berkaca dari realita dan pemikiran tersebut, maka tentunya pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melalui proses perenungan dan kajian secara mendalam dimana penanganan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan harus dilaksanakan secara integral. Pengaturan tersebut juga sekaligus merupakan terobosan atau inovasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang selama ini menganut asas diferensiasi fungsional atau dapat dimaknai sebagai pembagian tugas dan wewenang aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian, pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dimaksud tentu tidak relevan dan tidak berdasarkan pada norma-norma pemberantasan korupsi.
Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan asas peradilan pidana, maka keberadaan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan pengejawantahan asas peradilan cepat.
Hal ini terbukti dari praktik yang terjadi selama ini dimana penanganan tindak pidana korupsi dalam satu atap seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK jauh lebih efektif dan efisien sehingga haruslah dianggap sebagai keuntungan tersendiri dalam penanganan korupsi yang pada umumnya membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk mengungkap modus operandi, para pelaku, dan aset hasil pidana.
Hal lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa gugatan ini diajukan di tengah adanya peningkatan kinerja Kejaksaan dalam penanggulangan perkara tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah-daerah, sebagaimana halnya tergambar secara jelas dari tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap Kejaksaan yang mencapai angka 80,6 berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia.
Secara logis, tingginya kepercayaan publik kepada Kejaksaan sebagai salah satu cermin aparat penegak hukum tentu harusnya memberikan optimisme bahwa penanggulangan korupsi akan menjadi lebih baik dan optimal sepanjang tidak adanya gangguan ataupun upaya-upaya pelemahan terhadap Kejaksaan secara institusional. Oleh karenanya tidak berlebihan pula apabila banyak praktisi maupun akademisi yang berpandangan bahwa pengajuan judicial review kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini adalah sebagai salah satu langkah untuk mengaburkan atau mengganggu penanganan tindak pidana korupsi yang tengah gencar dilakukan oleh Kejaksaan pada saat ini.
Penulis: Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.Hum.
(Akademisi/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)